Khalifah: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 149: | Baris 149: | ||
== Keruntuhan kekhalifahan == |
== Keruntuhan kekhalifahan == |
||
Setelah Sultan Abdül Hamid II digulingkan pada 1909, dua sultan penerusnya hampir kehilangan kekuatan politik sepenuhnya dan hanya berperan sebagai lambang kepala negara semata tanpa kekuasaan yang nyata. Kesultanan Utsmani kehilangan sebagian besar wilayahnya setelah kalah dalam [[Perang Dunia I]], menjadikan hanya menguasai kawasan Anatolia dan ujung tenggara Balkan. [[Istambul]] (Konstantinopel) dikuasai [[Britania Raya]] setelahnya, menciptakan sebuah kevakuman politik dengan menawan banyak pejabat negara dan menutup kantor-kantor pemerintahan dengan paksa. |
|||
Tepatnya pada tanggal 3 Maret 1924, keruntuhan kekhalifahanan terakhir, Kekhalifahan Turki Usmaniyah, terjadi akibat adanya perseteruan di antara kaum [[nasionalis]] dan agamais dalam masalah kemunduran ekonomi Turki. |
|||
Kekalahan Utsmani menimbulkan reaksi yang disebut [[Gerakan Khilafat]] sebagai bentuk kekhawatiran akan kesatuan umat Islam. Meski gerakan ini didengungkan di berbagai belahan dunia Islam, kegiatannya paling banyak dilangsungkan di India sehingga juga disebut Gerakan Muslim India. Sebagai pemenang perang, pihak Eropa menjanjikan untuk melindungi status penguasa Utsmani sebagai khalifah, tetapi [[Perjanjian Sèvres]] yang ditandatangani pada 1920 menjadikan kawasan Iraq, [[Syam]], dan Mesir diserahkan pada negara-negara Eropa. |
|||
Setelah menguasai [[Istambul]] pasca-Perang Dunia I, [[Inggris]] menciptakan sebuah kevakuman politik dengan menawan banyak pejabat negara dan menutup kantor-kantor dengan paksa sehingga bantuan khalifah dan pemerintahannya tersendat. Kekacauan terjadi di dalam negeri, sementara opini umum mulai menyudutkan pemerintahan khalifah yang semakin lemah dan memihak kaum nasionalis. Situasi ini dimanfaatkan [[Mustafa Kemal Atatürk|Mustafa Kemal Pasha (Atatürk)]] untuk membentuk Dewan Perwakilan Nasional - dan ia menobatkan diri sebagai ketuanya - sehingga ada dua pemerintahan saat itu; pemerintahan khilafah di [[Istambul]] dan pemerintahan Dewan Perwakilan Nasional di [[Ankara]]. Walau kedudukannya tambah kuat, Mustafa Kemal Pasha belum berani membubarkan khilafah. Dewan Perwakilan Nasional hanya mengusulkan konsep yang memisahkan khilafah dengan pemerintahan. Namun, setelah perdebatan panjang di Dewan Perwakilan Nasional, konsep ini ditolak. Pengusulnya pun mencari alasan membubarkan Dewan Perwakilan Nasional dengan melibatkannya dalam berbagai kasus pertumpahan darah. Setelah memuncaknya krisis, Dewan Perwakilan Nasional ini diusulkan agar mengangkat Mustafa Kemal Pasha sebagai ketua [[parlemen]], yang diharap bisa menyelesaikan kondisi kritis ini. |
|||
Pada 1 November 1922, [[Majelis Agung Nasional Turki]] secara resmi membubarkan Kesultanan Utsmani. Sultan terakhirnya, [[Mehmed VI]], diasingkan ke Malta. Setelah pembubaran Utsmani, [[Republik Turki]] yang berasaskan sekuler didirikan dengan Mustafa Kemal sebagai presiden pertamanya. |
|||
Setelah resmi dipilih jadi ketua [[parlemen]], Mustafa Kemal Pasha mengumumkan kebijakannya, yaitu mengubah sistem khilafah dengan [[republik]] yang dipimpin seorang [[presiden]] yang dipilih lewat [[Pemilu]]. Tanggal [[29 November]] [[1923]], ia dipilih parlemen sebagai presiden pertama [[Turki]]. Namun ambisinya untuk membubarkan khilafah saat itu, yang telah lemah dan digerogoti korupsi, terintangi; Ia dianggap [[murtad]], dan beberapa kelompok pendukung [[Abdul Mejid II]] terus berusaha mendukung pemerintahannya. Ancaman ini tak menyurutkan langkah Mustafa Kemal Pasha. Malahan, ia menyerang balik dengan taktik politik dan pemikirannya yang menyebut bahwa penentang sistem [[republik]] ialah pengkhianat bangsa dan ia kemudian melakukan beberapa langkah kontroversial untuk mempertahankan sistem pemerintahannya. Misalnya, Khalifah digambarkan sebagai sekutu asing yang harus dienyahkan. |
|||
Meski demikian, Mustafa Kemal tidak berani membubarkan kekhalifahan demi menjaga dukungan rakyat. Meski sudah kehilangan peran politiknya sejak lama, khalifah tetap dipandang sebagai lambang pemersatu umat Islam Sunni seluruh dunia. Pembubaran kesultanan juga lebih mudah lantaran keberlangsungan kekhalifahan saat itu menyenangkan para pendukung kesultanan. Pada 17 November 1922, Majelis Agung Nasional Turki mengangkat sepupu Mehmed VI sebagai [[Abdul Mejid II|Khalifah Abdül Mejid II]]. Hal ini menjadikan Abdül Mejid II sebagai satu-satunya khalifah dari Wangsa Utsmani yang tidak merangkap sebagai sultan. |
|||
Setelah suasana negara kondusif, Mustafa Kemal Pasha mengadakan sidang Dewan Perwakilan Nasional (yang kemudian disebut dengan "Kepresidenan Urusan Agama" atau sering disebut dengan "Diyaniah"). Pada tanggal [[3 Maret]] [[1924]], ia memecat khalifah sekaligus membubarkan sistem kekhalifahan dan menghapuskan hukum Islam dari negara. Hal inilah yang kemudian dianggap sebagai keruntuhan kekhalifahan Islam. |
|||
Saat ini, Diyaniah berfungsi sebagai entitas dari lembaga Shaikh al-Islam/Kekhalifahan [http://www.diyanet.gov.tr/english/tanitim.asp?id=4]. Mereka bertugas untuk: "memberikan pelayanan religius kepada orang Turki dan Muslim di dalam dan di luar negara Turki". Diyainah memiliki kantor pusat di [[Ankara|Ankara, Turki]]. |
|||
Keadaan ini menjadikan keadaan di Turki terbelah dengan pemerintahan republik yang baru di satu sisi dan pemerintahan Islam yang dikepalai khalifah di sisi lain. Khalifah memiliki perbendaharaan pribadi dan pelayanan pribadi, termasuk personel militer. Abdül Mejid II juga menerima duta asing, juga turut serta dalam upacara dan perayaan resmi. Mustafa Kemal mengkhawatirkan bahwa Abdül Mejid II nantinya akan memegang kendali urusan negara selayaknya seorang sultan. |
|||
Diyaniah adalah sebuah lembaga yang mewarisi semua sumber-sumber yang berhubungan dengan hal-hal religius dari Kekaisaran Ottoman, termasuk semua arsip kekhalifahan yang telah runtuh tersebut. Saat ini, Diyainah merupakan otoritas tertinggi Muslim Sunni. Diyainah juga memiliki kantor cabang di [[Eropa]] ([[Jerman]]). |
|||
Dalam keadaan seperti ini, Maulana Mohammad Ali dan Maulana Shaukat Ali yang merupakan pemimpin Gerakan Khilafat menyebarkan pamflet yang menyerukan rakyat Turki untuk mendukung kekhalifahan demi kepentingan Islam. Oleh pihak republik, hal ini dipandang sebagai campur tangan pihak asing yang dapat membahayakan keamanan negara. Hal ini menjadi pembenaran Mustafa Kemal untuk mengakhiri kekhalifahan. Pada 3 Maret 1924, Majelis Agung Nasional Turki membubarkan kekhalifahan dan mengasingkan Abdül Mejid II beserta para pangeran dan putri Wangsa Utsmaniyah dari Republik Turki. |
|||
Perbedaan utama antara kekhalifahan dengan Diyainah adalah Dinaiyah, tidak seperti kekhalifahan yang mengurusi masalah negara, hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan. Hal ini sesuai dengan prinsip sekularisme [[Turki]] yang memisahkan urusan Agama dengan urusan negara. |
|||
=== Pasca pembubaran kekhalifahan === |
|||
Sempat muncul keinginan dan gerakan untuk mengendirikan kembali kekhalifahan setelah runtuhnya [[Kekaisaran Ottoman]], tetapi tak ada satupun yang berhasil. [[Hussein bin Ali]], seorang gubernur [[Hejaz]] pada masa Kekaisaran Ottoman yang pernah membantu [[Britania raya]] pada masa [[Perang Dunia I]] serta melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Istambul, mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah dua hari setelah keruntuhan Ottoman. Tetapi klaimnya tersebut ditolak, dan tak lama kemudian ia di usir dari tanah Arab. Sultan Ottoman terakhir [[Mehmed VI]] juga melakukan hal yang sama untuk mengangkat kembali dirinya sebagai Khalifah di Hejaz, tetapi lagi-lagi usaha tersebut gagal. Sebuah pertemuan diadakan di [[Kairo]] pada tahun [[1926]] untuk mendiskusikan pendirian kembali kekhalifahan. Tetapi, hanya sedikit negara Muslim yang berpartisipasi dan mengimplentasikan hasil dari pertemuan tersebut. |
|||
Banyak pihak mempertanyakan keabsahan pembubaran kekhalifahan oleh pihak Turki secara sepihak. Syarif Makkah, [[Husain bin Ali]], mengklaim gelar khalifah untuk dirinya sendiri. Namun pengakuannya tidak diterima oleh semua umat Muslim. Setelah Husain turun takhta, putranya tidak melanjutkan klaim ayahnya sebagai khalifah. |
|||
Pada 1926, diselenggarakan pertemuan di Kairo terkait upaya untuk kembali menegakkan kekhalifahan, tetapi banyak negara Muslim yang tidak hadir dan tidak ada tindakan nyata setelah pertemuan tersebut. |
|||
=== Gerakan Khilafat === |
|||
Pada |
Pada perkembangan selanjutnya, gelar ''Amir al-Mukmin'' disandang oleh [[Raja Maroko]] dan [[Mohammed Omar|Mullah Mohammed Omar]], pemimpin rezim [[Taliban]] di [[Afganistan]], tetapi kebanyakan Muslim di luar daerah kekuasaan mereka menolak untuk mengakuinya. Saat ini banyak pecahan negara-negara muslim yang membentuk [[Organisasi Konferensi Islam]] atau [[OKI]], sebuah organisasi internasional dengan pengaruh yang terbatas yang didirikan pada tahun 1969 beranggotakan negara-negara mayoritas Muslim. |
||
== Landasan agama == |
== Landasan agama == |
||
Revisi per 10 Januari 2019 15.12
Netralitas artikel ini dipertanyakan. |
| Bagian dari seri |
| Islam |
|---|
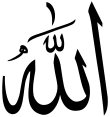 |
Khalifah (bahasa Arab: خَليفة; Khalīfah) adalah gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad dalam kepemimpinan umat Islam. Wilayah kewenangan khalifah disebut kekhalifahan atau khilafah (bahasa Arab: خِلافة). Gelar lain yang juga melekat dengan khalifah adalah amīr al-mu'minīn (أمير المؤمنين) atau "pemimpin orang yang beriman", meski pada keberjalanannya, gelar ini juga disandang oleh pemimpin Muslim selain khalifah.
Sepanjang sejarahnya, peran khalifah dan bentuk kekhalifahan memiliki beragam corak yang sangat dipengaruhi keadaan politik dan keagamaan di masa tersebut. Dilihat dari latar belakang khalifah, kekhalifahan dibagi ke dalam empat periode: Kekhalifahan Rasyidin (632–661), Kekhalifahan Umayyah (661–750), Kekhalifahan Abbasiyah (750–1258 dan 1261–1517), dan Kekhalifahan Utsmaniyah (1517–1924).
Kekhalifahan dimulai seiring diangkatnya Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam tepat setelah meninggalnya Nabi Muhammad pada tahun 632. Abu Bakar dan tiga penerusnya, semuanya sahabat Nabi dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad, dikelompokkan sebagai Khulafaur Rasyidin atau Kekhalifahan Rasyidin. Pemilihan keempat khalifah pertama ini didasarkan melalui musyawarah dan kepantasan pribadi calon sehingga Kekhalifahan Rasyidin kerap dipandang sebagai bentuk awal demokrasi Islam.
Setelah perang saudara pertama di penghujung masa Kekhalifahan Rasyidin, Hasan bin 'Ali menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Mu'awiyah yang kemudian mengubah bentuk kekhalifahan menjadi monarki-dinasti, menandai dimulainya masa Kekhalifahan Umayyah. Berpusat di Damaskus, Bani Umayyah memegang tampuk kekhalifahan selama hampir seabad sebelum akhirnya digulingkan kelompok Abbasiyah yang mendirikan kekhalifahan-dinasti mereka sendiri mulai tahun 750. Berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin atau Umayyah, khalifah pada masa Abbasiyah tidak lagi memimpin secara langsung seluruh wilayah dunia Islam dan wilayah kekuasaannya hanya berkisar di kawasan Mesopotamia. Beberapa kepala negara Muslim (bergelar amir atau sultan) memimpin wilayah kekuasaan mereka secara mandiri tanpa campur tangan khalifah. Meski begitu, khalifah tetap dipandang sebagai pemimpin dunia Islam secara keseluruhan dan kepala negara Muslim yang lain memberikan ketundukkan mereka secara simbolis kepada khalifah. Berbeda dengan Umayyah yang sangat bercorak Arab, Abbasiyah yang berpusat di kawasan Mesopotamia memberikan corak Persia yang kental pada kekhalifahan.
Fungsi khalifah sebagai kepala negara lenyap seiring jatuhnya Baghdad oleh Mongol pada 1258. Keturunan Abbasiyah yang tersisa melanjutkan tampuk kekhalifahan di Mesir yang saat itu di bawah kekuasaan Kesultanan Mamluk. Tanpa wilayah kekuasaan dan kekuatan politik yang memadai, khalifah hanya berperan sebagai pemersatu umat Islam secara simbolis sehingga khalifah pada periode ini dikenal sebagai "khalifah bayangan."
Setelah Kesultanan Mamluk ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmani pada 1517, pemimpin Utsmani mengambil gelar khalifah untuk mereka sendiri. Gelar khalifah terbatas hanya sebagai pemimpin simbolis dunia Islam setelah 1258 dan hal itu tetap tidak berubah pada masa Utsmani. Para penguasa Utsmani memiliki kekuasaan karena kedudukan mereka sebagai sultan dan padisyah (kaisar), bukan karena status mereka sebagai khalifah. Pada praktiknya, para penguasa Utsmani terbilang sangat jarang menggunakan gelar khalifah (pemimpin umat Islam) mereka dalam perpolitikan dalam dan luar negeri dan lebih sering menggunakan status mereka sebagai sultan dan padisyah (kepala negara Utsmani). Gelar khalifah mulai digunakan penguasa Utsmani pada saat Perjanjian Küçük Kaynarca, untuk menegaskan kedudukannya sebagai pelindung umat Islam di Rusia. Sultan Abdül Hamid II merupakan penguasa Utsmani yang paling sering menggunakan gelar khalifah dalam upayanya menggalang persatuan di dunia Islam untuk menghadapi imperialisme Barat.
Pada November 1922, Majelis Agung Nasional Turki membubarkan Kesultanan Utsmani dan sultan terakhirnya, Mehmed VI, diasingkan ke Malta. Meski begitu, Mustafa Kemal belum berani membubarkan kekhalifahan demi menjaga dukungan masyarakat, juga karena kekhalifahan adalah lambang pemersatu umat Islam Sunni seluruh dunia, berbeda dengan Kesultanan Utsmani yang merupakan sebatas negara. Majelis Agung Nasional Turki kemudian mengangkat sepupu Mehmed VI sebagai Khalifah Abdül Mejid II pada 19 November 1922. Abdül Mejid II merupakan satu-satunya khalifah dari Wangsa Utsmani yang tidak merangkap sebagai sultan. Namun karena khawatir Abdül Mejid II akan menggunakan statusnya sebagai khalifah untuk campur tangan dalam urusan dalam dan luar negeri Turki sebagaimana yang dilakukan para Sultan Utsmani terdahulu, Majelis Agung Nasional Turki akhirnya membubarkan kekhalifahan pada 3 Maret 1924, menjadikan Abdül Mejid II sebagai khalifah terakhir. Negara-negara Muslim mempertanyakan keabsahan pembubaran kekhalifahan oleh pihak Turki dan terdapat beberapa pertemuan para tokoh Muslim terkait keberlangsungan kekhalifahan, tetapi tidak ada kesepakatan bersama yang dapat dicapai.
Etimologi
Kata "Khalifah" sendiri dapat diterjemahkan sebagai "pengganti" atau "perwakilan". Dalam Al-Qur'an, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad sebagai Imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikannya sebagai penguasa sebuah entitas kedaulatan Islam (negara). Sebagaimana diketahui bahwa Muhammad selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai Imam, Penguasa, Panglima Perang, dan lain sebagainya.
Peran dan kedudukan khalifah

Kebanyakan akademisi menyetujui bahwa Nabi Muhammad tidak secara langsung menyarankan atau memerintahkan pembentukan kekhalifahan Islam setelah kematiannya. Permasalahan yang dihadapi ketika itu adalah: siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad, dan sebesar apa kekuasaan yang akan didapatkannya?
Pengganti Nabi Muhammad
Fred M. Donner, dalam bukunya The Early Islamic Conquests (1981), berpendapat bahwa kebiasaan bangsa Arab ketika itu adalah untuk mengumpulkan para tokoh masyarakat dari suatu keluarga (bani dalam bahasa arab), atau suku, untuk bermusyawarah dan memilih pemimpin dari salah satu di antara mereka. Tidak ada prosedur spesifik dalam syuro atau musyawarah ini. Para kandidat biasanya memiliki garis keturunan dari pemimpin sebelumnya, walaupun hanya merupakan keluarga jauh.
Hingga pada tiba saatnya Nabi Muhammad meninggal, kaum Muslim berdebat tentang siapa yang berhak untuk menjadi penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya rasul, hingga saat ini apa yang dibicarakan di dalam masa tenggang itu masih menjadi kontroversi di kalangan kaum Muslim, namun dapat dipastikan bahwa mayoritas kaum muslim yang hadir dalam musyawarah saat itu meyakini bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah penerus kepemimpinan Islam yang akan menggantikan rasul karena sebelum Nabi Muhammad meninggal, ia dipercaya untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai imam shalat, dan akhirnya Abu Bakar pun terpilih menjadi Khalifah pertama dalam sejarah Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad.
Namun beberapa kalangan dari kaum Muslim Mekkah dan Madinah saat itu meyakini bahwa Nabi Muhammad telah memberikan banyak indikasi yang menunjukan bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantunya, sebagai pengganti dirinya. Mereka mengatakan bahwa Abū Bakar merebut kekuasaan dengan kekuatan dan kelicikan[butuh rujukan]. Semua Khalifah sebelum Ali juga dianggap melakukan hal yang sama oleh kalangan ini, hal inilah yang memicu munculnya kaum Syiah belakangan pada masa kekhalifahan Muawiyah, lebih tepatnya setelah masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib berakhir.
Kekuasaan
"Siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad" bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi umat Islam saat itu; mereka juga perlu mengklarifikasi seberapa besar kekuasaan pengganti sang nabi. Muhammad, selama masa hidupnya, tidak hanya berperan sebagai pemimpin umat islam, tetapi sebagai nabi dan pemberi keputusan untuk umat Islam. Semua hukum dan praktik spiritual ditentukan sesuai dengan yang disampaikan Nabi Muhammad. Musyawarah dilakukan pada persoalan ini untuk menentukan seberapa besar kekuasaan seorang Khalifah.
Tidak satu pun dari para khalifah yang mendapatkan wahyu dari Allah, karena Nabi Muhammad adalah nabi dan penyampai wahyu terakhir di muka bumi, tidak satu pun di antara mereka yang menyebut diri mereka sendiri sebagai nabī atau rasul. Untuk mengatasinya, wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kemudian ditulis dan dikumpulkan menjadi Al-quran, dijadikan patokan dan sumber utama hukum Islam, dan menjadi batas kekuasaan khalifah Islam. Artinya, Khalifah adalah seseorang pemimpin yang tunduk pada Al-Qur'an dan Hadis, dan kekuasaannya pun dibatasi oleh Al-Qur'an dan Hadis.
Bagaimanapun, ada beberapa bukti yang menunjukan bahwa khalifah mempercayai bahwa mereka mempunyai otoritas untuk memutuskan beberapa hal yang tidak tercantum dalam al-Quran. Mereka juga mempercayai bahwa mereka adalah pempimpin spiritual umat islam, dan mengharapkan "kepatuhan kepada khalifah" sebagai ciri seorang muslim sejati. Sarjana modern Patricia Crone dan Martin Hinds, dalam bukunya God's Caliph, menggarisbawahi bahwa fakta tersebut membuat khalifah menjadi begitu penting dalam pandangan dunia Islam ketika itu. Mereka berpendapat bahwa pandangan tersebut kemudian hilang secara perlahan-lahan seiring dengan bertambah kuatnya pengaruh ulama di kalangan umat Islam. Kaum Muslim beranggapan bahwa ulama sama berhaknya menentukan apa yang dianggap legal dan baik di kalangan umat, sesuai dengan hadis yang menyebutkan bahwa suatu kaum akan ditinggalkan oleh Allah ketika mereka meninggalkan para ulama. Pemimpin umat Islam yang paling tepat, menurut pendapat para ulama, adalah pemimpin yang menjalankan saran-saran spiritual dari para ulama, sementara para khilafah hanya mengurusi hal-hal yang bersifat duniawi sehingga mengakibatkan perdebatan di antara keduanya. Perselisihan pendapat antara Khalifah dan para ulama tersebut menjadi konflik yang berlarut-larut dalam beberapa bagian sejarah kekhalifahan Islam. Namun akhirnya, konflik ini berakhir dengan kemenangan para ulama.[butuh rujukan] Kekuasaan Khalifah selanjutnya menjadi terbatas pada hal yang bersifat keduniawian. Khalifah hanya dapat dianggap menjadi "Khalifah yang benar" apabila ia menjalankan saran spiritual para ulama.[butuh rujukan] Patricia Crone dan Martin Hinds juga berpendapat bahwa muslim Syiah, dengan pandangan yang berlebihan kepada para imam, tetap menjaga kepercayaan murni umat islam, namun tidak semua ilmuwan setuju akan hal ini.
Kebanyakan Muslim Sunni saat ini mempercayai bahwa para khalifah tidak selamanya hanya menjadi pemimpin masalah duniawi, dan ulama sepenuhnya bertanggung jawab atas arah spiritual umat islam dan hukum syariah umat islam. Mereka menyebut empat Khalifah pertama sebagai Khulafaur Rasyidin, Khalifah yang diberi petunjuk, karena mereka menjalankan dan berpegang pada hukum yang terdapat pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad dalam segala hal. Mereka juga mempercayai bahwa sekali khalifah dipilih untuk memimpin, maka sepanjang hidupnya ia akan memerintah kecuali jika ia keluar dari aturan syariat.
Karakter kepemimpinan
Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa karakter pemimpin Islam ialah menganggap bahwa otoritas dan kekuasaan yang dimilikinya adalah sebuah kepercayaan (amanah) dari umat Islam dan bukan kekuasaan yang mutlak dan absolut. Hal ini didasarkan pada hadis yang berbunyi:
"It (sovereignty) is a trust, and on the Day of Judgment it will be a thing of sorrow and humiliation except for those who were deserving of it and did well."
Hal ini sangat kontras dengan keadaan Eropa saat itu di mana kekuasaan raja sangat absolut dan mutlak.[1]
Peranan seorang kalifah telah ditulis dalam banyak sekali literatur oleh teolog islam. Imam Najm al-Din al-Nasafi menggambarkan khalifah sebagai berikut:
"Umat Islam tidak berdaya tanpa seorang pemimpin (imam, dalam hal ini khalifah) yang dapat memimpin mereka untuk menentukan keputusan, memelihara dan menjaga daerah perbatasan, memperkuat angkatan bersenjata (untuk pertahanan negara), menerima zakat mereka (untuk kemudian dibagikan), menurunkan tingkat perampokan dan pencurian, menjaga ibadah pada hari jumat (salat jumat) dan hari raya, menghilangkan perselisihan di antara sesama, menghakimi dengan adil, menikahkan wanita yang tak memiliki wali. Sebuah keharusan bagi pemimpin untuk terbuka dan berbicara di depan orang yang dipimpinnya, tidak bersembunyi dan jauh dari rakyatnya.
Ia sebaiknya berasal dari kaum Quraish dan bukan kaum lainnya, tetapi tidak harus dikhususkan untuk Bani Hasyim atau anak-anak Ali. Pemimpin bukanlah seseorang yang suci dari dosa, dan bukan pula seorang yang paling jenius pada masanya, tetapi ia adalah seorang yang memiliki kemampuan administratif dan memerintah, mampu dan tegas dalam mengeluarkan keputusan dan mampu menjaga hukum-hukum Islam untuk melindungi orang-orang yang terzalimi. Dan mampu memimpin dengan arif dan demokratif.
Ibnu Khaldun kemudian menegaskan hal ini dan menjelaskan lebih jauh tentang kepemimpinan kekhahalifah secara lebih singkat:
"Kekhalifahan harus mampu menggerakan umat untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam dan menyeimbangkan kewajiban di dunia dan akhirat. (Kewajiban di dunia) harus seimbang (dengan kewajiban untuk akhirat), seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, semua kepentingan dunia harus mempertimbangkan keuntungan untuk kepentingan akhirat. Singkatnya, (Kekhalifahan) pada kenyataannya menggantikan Nabi Muhammad, beserta sebagian tugasnya, untuk melindungi agama dan menjalankan kekuasaan politik di dunia."
Pencabutan gelar
Kebanyakan ulama menolak pencabutan gelar Khalifah apabila sudah terpilih. Tetapi fakta yang terjadi adalah sebaliknya, banyak pemberontakan pada masa kekhalifahan, seperti Imam Husain yang melakukan revolusi di Karbala melawan tirani Yazid atau pengkhianatan Ibnu al-Zubayr kepada Yazid, untuk kebanyakan bagian telah terbatas keberadaannya.[2]
Dr. Abdul Aziz Islahi berpendapat dalam masalah ini:
Mengikuti para filsuf Yunani, St. Thomas Aquinas juga menggunakan sudut pandang ini, William Archibald Dunning berkomentar: "Berhubungan dengan aksi-aksi individual dalam menjatuhkan pemerintahan tirani, dia (Aquinas) menemukan bahwa lebih sering orang jahat melakukan pemberontakan dibandingkan orang baik. Karena orang-orang jahat berpendapat bahwa pemerintahan raja-raja tidak kurang beratnya daripada para tiran (raja lalim, penindas), pengakuan hak-hak pribadi warga untuk membunuh para tiran lebih menyangkut lebih besarnya peluang untuk kehilangan seorang raja daripada membebaskan diri dari seorang tiran."
Khalifah utama
Khulafaur Rasyidin

Segera setelah Nabi Muhammad mangkat pada 632, Abu Bakar diangkat sebagai pemimpin umat Islam di Masjid Nabawi. Dikenal dengan sebutan Ash-Shiddiq (bahasa Arab: اَلـصِّـدِّيْـق, "Terpercaya"), Abu Bakar termasuk salah satu pemeluk Islam awal dan melalui putrinya, 'Aisyah, dia juga merupakan mertua Nabi. Masa kekuasaannya yang singkat dikerahkan untuk menumpas pemberontakan dari berbagai suku Arab yang merasa tidak punya tanggung jawab kesetiaan lagi pada pihak Madinah sepeninggal Nabi Muhammad.[3] Abu Bakar sangat menjaga agar kebijakan yang dia ambil tidak berbeda dengan Nabi Muhammad.
Setelah Abu Bakar mangkat pada 634 dengan meninggalkan keadaan kekhalifahan yang mulai stabil, 'Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah kedua. Sebagaimana Abu Bakar, 'Umar juga merupakan ayah mertua Nabi melalui Hafshah. Di masanya, 'Umar melakukan berbagai pembaharuan dan perluasan. Tapal batas kekhalifahan meluas keluar dari semenanjung Arabia, mengakhiri riwayat Kekaisaran Sasaniyah dan mengambil alih dua pertiga wilayah Kekaisaran Romawi Timur.[4] Segala capaiannya menjadikan 'Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah.[5]

'Utsman bin 'Affan meneruskan tampuk kekhalifahan sepeninggal 'Umar dan berbeda dengan pendahulunya, 'Utsman lebih memberikan kekuasaan otonomi yang lebih longgar pada bawahannya. Hal ini menjadikan perluasan wilayah kekhalifahan dapat dilangsungkan secara lebih mandiri, sehingga dapat mencapai wilayah yang lebih jauh. Pada masanya, kekhalifahan sudah mencapai sebagian wilayah Khorasan Raya (kawasan Asia Tengah) di batas timur.[6] Di masanya, masyarakat menjadi lebih makmur dalam masalah ekonomi dan menikmati kebebasan yang lebih besar di bidang politik. Namun 'Utsman juga dikritik karena lebih mendahulukan keluarga besarnya untuk mengisi berbagai kedudukan penting, menjadikan munculnya gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada pengepungan rumahnya pada tahun 656. 'Utsman yang tidak ingin menjadi penyebab perang saudara menolak bantuan militer dari kerabat dan pihak lain, menjadikannya terbunuh di akhir pengepungan.[7]
'Ali mewarisi kedudukan khalifah setelahnya. Masa kekuasaannya merupakan salah satu masa-masa tersulit dalam sejarah Islam lantaran pada saat inilah terjadi perang saudara Islam pertama yang berawal dari terbunuhnya 'Utsman. 'Ali dibunuh kelompok Khawarij[8][9][10] dan putranya, Hasan, diangkat menjadi khalifah berikutnya pada 661. Namun beberapa bulan setelahnya, Hasan menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Mu'awiyah[11][12] demi menghindari perang saudara lebih lanjut.[13]
Di wilayah yang dulu dikuasai Kekaisaran Sasaniyah dan Romawi, khalifah menurunkan pajak dan memberikan kelonggaran otonomi melalui gubernur pilihan mereka. Berkebalikan dengan Romawi, khalifah memberikan kebebasan beragama yang lebih luas dan memberikan masyarakat non-Muslim hak otonomi untuk mengatur urusan mereka sendiri. Segala kebijakan ini mengangkat moral dan kepercayaan masyarakat yang selama ini terbebani dengan pajak tinggi dan segala kekacauan yang diakibatkan Perang Romawi-Persia yang berturut-turut.[14]
Wangsa Umayyah
Setelah Hasan bin 'Ali turun takhta pada 661, Mu'awiyah berkuasa sebagai khalifah. Penetapan putranya menjadi putra mahkota menjadikan bentuk kekhalifahan berubah menjadi monarki dinasti yang kedudukan kepala negaranya diwariskan hanya di antara keluarga besar penguasa sebelumnya, dan dari sinilah Wangsa Umayyah lahir.[15] Secara silsilah, khalifah dari Wangsa Umayyah terbagi menjadi dua:
- Kelompok Sufyani, yakni yang merupakan keturunan dari Abu Sufyan bin Harb. Ada tiga orang khalifah yang berasal dari garis Sufyani.
- Kelompok Marwani, merujuk kepada Marwan bin al-Hakam dan keturunannya. Ada sebelas orang khalifah yang berasal dari garis Marwani.
Abu Sufyan dan Al-Hakam (ayah Marwan) adalah cucu dari Umayyah bin 'Abd asy-Syams dan dari sini nama Bani Umayyah ditetapkan.

Wangsa Umayyah melanjutkan perluasan wilayah kekhalifahan, meliputi kawasan Transoxiana, Sindh, Arab Maghrib, dan Al-Andalusia, menjadikan kekhalifahan saat itu sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia yang pernah ada, baik dari segi luas wilayah maupun populasi, dengan luas mencakup 11,100,000 km2 dengan penduduk sekitar 33 juta jiwa.[16]
Pada masa Umayyah, bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi dari kekhalifahan yang terdiri dari penduduk multi-etnis tersebut. Perpindahan agama besar-besaran menjadi mualaf juga terjadi pada masa Umayyah. Pembangunan banyak bangunan Muslim bersejarah juga dibangun pada masa ini, seperti Kubah Shakhrah di kompleks Masjid Al Aqsha dan Masjid Agung Damaskus.[17] Umayyah juga memberikan kebebasan beragama pada umat non-Muslim dan meskipun mereka tidak bisa menempati hierarki teratas lembaga-lembaga penting, banyak yang menjadi pejabat tinggi di pemerintahan, menjadikan sebagian kalangan Muslim menilai bahwa Wangsa Umayyah terlalu sekuler.[18] Dari semua khalifah dari Wangsa Umayyah, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dikenal yang paling saleh dan kerap dipandang sebagai khulafaur rasyidin kelima.
Terlepas dari segala capaiannya, Umayyah dikritik karena sangat menganakemaskan Muslim Arab dibandingkan Muslim dari etnis lain yang jumlahnya semakin besar. Pembunuhan Husain dalam Pertempuran Karbala pada 680 oleh pihak Umayyah menjadikan perpecahan antara Sunni dan Syiah semakin nyata.[19] Perang saudara juga melanda kekhalifahan mulai tahun 744, menjadikan kendali Wangsa Umayyah atas negara melemah. Gelombang non-Arab yang menjadi mualaf juga mengubah keadaan dalam negeri kekhalifahan karena banyak dari mereka yang lebih terdidik dari bangsa Arab sendiri, sehingga mengubah keadaan politik dalam kekhalifahan.[20] Pada akhirnya, pendukung Bani Hasyim dan garis keturunan 'Ali berhasil meruntuhkan kekuasaan Umayyah pada 750. Banyak anggota Wangsa Umayyah yang dibunuh setelahnya, di antaranya adalah Marwan bin Muhammad yang merupakan khalifah terakhir dari Wangsa Umayyah di Syam. Di antara anggota Wangsa Umayyah yang selamat adalah 'Abdurrahman ad-Dakhil yang mengungsi ke Al-Andalus dan berkuasa di sana.
Wangsa Abbasyiah

Wangsa Abbasiyah memegang tampuk kekhalifahan setelah kekuasaan Umayyah di Syam runtuh pada 750. Keluarga besar ini merupakan keturunan dari 'Abbas bin 'Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Berpusat di kawasan Mesopotamia, Abbasiyah mengadopsi besar-besaran kebudayaan Persia ke dalam tubuh kekhalifahan.[21]
Pada keberjalanannya, wilayah kekuasaan khalifah pada masa Abbasiyah perlahan semakin menyusut hingga hanya di sekitar Mesopotamia. Banyak pihak mendirikan dinasti mereka sendiri dan menguasai suatu bagian dari dunia Islam seperti Wangsa Idrisiyyah yang menguasai Maroko, Aghlabiyyah yang memerintah di Ifriqiya, Dinasti Thuluniyah di Mesir dan Palestina, Bani Buwaih di Iran, Dinasti Samaniyah di Transoxiana, dan Seljuk yang menguasai wilayah yang sangat luas di kawasan Timur Tengah, Kaukasus, dan Asia Tengah. Sebagian dari penguasa dinasti ini menggunakan gelar amir atau bahkan syahansyah (raja diraja), gelar penguasa Persia pra-Islam. Pada masa ini mulai muncul gelar sultan yang mulai digunakan untuk kepala negara Muslim dan mulai menggeser penggunaan gelar amir. Meski banyak dari dinasti baru ini menguasai wilayah yang jauh lebih luas dari khalifah sendiri dan memerintah secara mandiri tanpa campur tangan khalifah, tetapi para amir dan sultan ini tetap mengakui kedaulatan khalifah atas mereka secara simbolis dan khalifah tetap dipandang sebagai pemimpin dunia Islam secara keseluruhan.

Salah satu hal paling menonjol pada masa kekuasaan Abbasiyah adalah dukungan besar mereka pada ilmu pengetahuan, salah satunya adalah pembangunan Baitul Hikmah, tempat penerjemahan, pengumpulan, penggabungan, dan pengembangan ilmu dari kebudayaan Romawi kuno, Tiongkok, Persia, India, Mesir, Afrika Utara, Yunani, dan Romawi Timur. Tidak hanya menjadi jantung kekuasaan dan pemerintahan, Baghdad, dan dunia Islam secara umum, juga menjelma menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, pendidikan, dan kesehatan pada masa yang dikenal dengan zaman keemasan Islam.[22] Pada berbagai bidang - matematika, astronomi, alkimia, kedokteran, optik, dan sebagainya - ilmuwan kekhalifahan berada pada garda terdepan dalam kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu.[23] Tidak hanya Muslim, ilmuwan dari kalangan non-Muslim juga turut memberi sumbangsih besar pada perkembangan ini.
Sastra dan literatur juga menjadi salah satu perhatian pada masa ini. Salah satu fiksi dari dunia Islam yang terkenal hingga saat ini, Seribu Satu Malam, yang merupakan kumpulan hikayat dan legenda, utamanya dikumpulkan pada masa Abbasiyah. Epik ini diyakini mulai terbentuk pada abad kesepuluh dan mencapai bentuk akhirnya pada abad keempat belas, jumlah dan jenis ceritanya berbeda-beda antara satu manuskrip dengan yang lain.[24] Syair Arab juga mencapai puncaknya pada masa ini. Salah satu syair terkenal dalam masalah percintaan adalah Layla dan Majnun.[25] Berbeda pada masa kekhalifahan sebelumnya, peran perempuan dalam ranah publik memudar di zaman Abbasiyah.[26] Budaya Persia pra-Islam, utamanya di kalangan atas, sangat ketat dalam melakukan pemisahan dunia laki-laki dan perempuan. Perempuan kalangan atas hidup dipingit dalam harem sebagai lambang kesucian dan tingginya status sosial keluarga yang bersangkutan.[27][28] Norma tersebut kemudian diadopsi Abbasiyah dan diikuti banyak umat Muslim pada masa-masa berikutnya.[28]
Meski banyak dinasti baru bermunculan dan menguasai wilayah yang cukup luas dari dunia Islam, umumnya khalifah masih memiliki peran sebagai kepala negara sebagai penguasa di kawasan Mesopotamia. Namun peran tersebut benar-benar lenyap setelah Hulagu Khan menduduki Baghdad pada 1258 dan membunuh Khalifah 'Abdullah Al-Musta'shim. Setelah peristiwa tersebut, dunia Islam mengalami kekosongan dari kepemimpinan khalifah selama sekitar tiga tahun. Dari naiknya Wangsa Abbasiyah setelah penggulingan Umayyah sampai jatuhnya Baghdad, terdapat 37 khalifah.
Bani Abbasiyah di Kairo
Setelah jatuhnya Baghdad, anggota Wangsa Abbasiyah yang selamat melarikan diri ke Mesir yang saat itu dikuasai Kesultanan Mamluk dan melanjutkan tampuk kekhalifahan di sana mulai tahun 1261. Namun berbeda saat masih di Baghdad, khalifah pada masa ini sama sekali tidak memiliki wilayah kekuasaan. Khalifah hanya mengurus permasalahan upacara dan keagamaan, sementara kekuatan politiknya sangat terbatas. Hal ini mejadikan khalifah sering terombang-ambing saat terjadi guncangan di pemerintahan Mesir. Tidak hanya mampu menunjuk khalifah baru yang dikehendaki, Sultan Mamluk bahkan mampu menggulingkan khalifah yang masih bertakhta saat terjadi perselisihan. Keadaan tersebut membuat khalifah pada periode ini sering disebut sebagai "khalifah bayangan".
Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1517 saat Kesultanan Utsmani yang berpusat di Konstantinopel menduduki Mesir, mengakhiri riwayat Mamluk. Khalifah saat itu, Muhammad Al-Mutawakkil, kemudian menyerahkan gelar khalifah kepada Sultan Utsmani, Selim I, menandai berakhirnya peran Wangsa Abbasiyah dan Quraisy sebagai khalifah. Dari tahun 1261 sampai penaklukkan Mesir oleh Utsmani, terdapat 17 khalifah. Di antara mereka, tiga khalifah menjabat sebanyak dua kali dan seorang khalifah menjabat sebanyak tiga kali. Secara keseluruhan, Wangsa Abbasiyah menyandang gelar khalifah selama hampir tujuh setengah abad, menjadikannya sebagai dinasti terlama yang memegang peran sebagai pemimpin dunia Islam ini sepanjang sejarah kekhalifahan.
Wangsa Utsmaniyah
Sebelum menjadi sebuah kekaisaran lintas benua, Utsmani awalnya adalah sebuah kadipaten kecil di kawasan Anatolia yang merupakan bawahan Kesultanan Seljuk. Saat Seljuk di ambang keruntuhan, kadipaten-kadipaten di Anatolia memerdekakan diri, termasuk kadipaten yang berada di bawah pimpinan Osman. Perlahan kadipaten yang dipimpin Osman dan keturunannya meluaskan wilayah dan menyatukan kadipaten yang lain, juga mulai meluaskan wilayahnya ke kawasan Balkan. Anak keturunannya menggunakan nama Osman untuk nama dinasti dan negara mereka yang semakin berkembang ini, yang kemudian dieja menjadi Utsman atau Utsmaniyah di Indonesia dan Ottoman di Barat.
Seiring menguatnya Kesultanan Utsmaniyah, para pemimpin mereka mulai mengklaim gelar khalifah untuk diri mereka sendiri, meski saat itu Wangsa Abbasiyah yang berada di Mesir masih memegang gelar ini dari generasi ke generasi. Klaim Utsmani atas kepemimpinan dunia Islam semakin menguat saat di bawah kepemimpinan Selim I, mereka menaklukkan Kesultanan Mamluk yang menguasai Mesir, Syam, dan Hijaz pada 1517. Wangsa Abbasiyah yang sejak tahun 1261 hidup dalam perlindungan Mamluk kemudian menyerahkan kedudukan mereka sebagai khalifah kepada pihak Utsmani, menjadikan Selim secara resmi sebagai khalifah pertama dari Wangsa Utsmani dan non-Arab.

Semenjak jatuhnya Baghdad, khalifah kehilangan fungsinya sebagai kepala negara dan hanya berperan sebagai pemimpin dunia Islam secara simbolis. Keadaan itu sebenarnya tetap tidak berubah pada masa Utsmani. Para penguasa Utsmani memiliki kekuatan politik atas kedudukan mereka sebagai sultan dan padisyah, bukan karena status mereka sebagai khalifah. Pada praktiknya, penguasa Utsmani sangat jarang menggunakan gelar khalifah pada percaturan politik di dalam dan luar negeri.
Di masa-masa selanjutnya, status penguasa Utsmani sebagai sultan melemah seiring bergesernya kendali pemerintahan di tangan wazir agung (perdana menteri) dan tokoh-tokoh terkemuka lain, tetapi fungsi khalifah justru makin berkembang. Gelar khalifah mulai digunakan saat Perjanjian Küçük Kaynarca (1774) yang dilakukan antara pihak Kesultanan Utsmani yang saat itu dipimpin Sultan Abdül Hamid I (berkuasa 1773 – 1789) dan Kekaisaran Rusia yang dipimpin Maharani Yekaterina II. Atas kemenangan Rusia atas Utsmani pada Perang Kozludzha, Utsmani dipaksa mengakui kedaulatan Kekhanan Krimea yang awalnya merupakan bawahan Utsmani dalam Perjanjian Küçük Kaynarca. Meski secara politik kehilangan Krimea, Abdül Hamid I menggunakan statusnya sebagai khalifah untuk menegaskan kepemimpinan keagamaannya atas Muslim Krimea. Yekaterina sendiri juga mengklaim sebagai pelindung umat Kristen Ortodoks di wilayah Utsmani pada perjanjian ini.[29] Dari perjanjian ini, status khalifah yang merupakan pemimpin dunia Islam mulai berkembang dari yang hanya sekadar simbol menjadi sebuah gelar yang memiliki kekuatan politik.
Di antara semua penguasa Utsmani, Sultan Abdül Hamid II (berkuasa 1876 – 1909) adalah yang paling sering menggunakan kedudukannya sebagai khalifah. Melalui statusnya sebagai khalifah, Abdül Hamid II berusaha menyatukan masyarakatnya yang multi-etnis atas dasar agama sebagai reaksi atas keadaan Utsmani yang semakin melemah dan terpecah,[30] juga menghimpun kekuatan dari seluruh dunia Islam untuk bersatu dalam melawan imperialisme Barat. Upayanya ini mengancam negara-negara Eropa, yakni Austria melalui Muslim Albania, Rusia melalui Tatar dan Kurdi, Prancis melalui Muslim Maroko, dan Britania Raya melalui Muslim India.[31] Upaya ini membuahkan hasil dalam beberapa hal. Setelah kemenangan Utsmani pada Perang Yunani-Turki, banyak umat Muslim memandang ini sebagai kemenangan Muslim. Pemberontakan dan penolakan penjajahan bangsa Eropa dilaporkan di suart kabar di berbagai wilayah Muslim.[31][32]
Meski berupaya menyatukan dunia Islam, atas permintaan duta Amerika untuk Utsmani Oscar Straus, Abdül Hamid II sepakat untuk menulis surat kepada Suku Suluk di Kesultanan Sulu agar mereka tidak melakukan perlawanan kepada Amerika. Hal ini menjadikan Muslim Sulu mengakui kedaulatan Amerika atas mereka.[33][33][34]
Terlepas dari segala hasil yang dicapai, upaya Abdül Hamid II dalam menyatukan masyarakat dengan identitas Islam tidak sepenuhnya berhasil. Hal ini karena besarnya jumlah populasi non-Muslim dan pengaruh Eropa atas Utsmani.[35] Setelah Abdül Hamid II digulingkan pada 1909, baik status Sultan Utsmani maupun khalifah kehilangan kekuatan politiknya.
Khalifah lain
Sebagai posisi pemimpin dunia Islam, idealnya hanya ada satu khalifah dalam satu masa. Namun sejarah menyaksikan bahwa dalam beberapa kurun waktu, terdapat beberapa pihak yang mengklaim gelar khalifah selain khalifah utama. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah reaksi penolakan atas kebijakan tertentu dari khalifah, kekuatan khalifah utama yang semakin memudar, atau pihak-pihak terkait merasa telah memiliki pengaruh yang cukup besar sehingga dipandang sebagai pemimpin dunia Islam. Mereka ini tidak dimasukkan ke dalam daftar khalifah utama atas dasar mereka klaim mereka sebagai khalifah tidak tersambung dengan khalifah sebelumnya.
Pernyataan pihak-pihak lain ini sebagai khalifah tidak berarti bahwa mereka menyatakan kedudukan mereka setara dengan khalifah utama. Khalifah adalah posisi untuk pemimpin dunia Islam dan harusnya hanya ada satu khalifah pada satu masa. Saat pihak ini menyatakan dirinya sebagai khalifah, mereka menyatakan kepemimpinan mereka atas seluruh umat Islam (terlepas wilayah kekuasaan mereka secara de facto) dan sekaligus memandang pihak lain yang juga menyandang gelar ini sebagai khalifah yang tidak sah.
'Abdullah bin Zubair
'Abdullah bin Zubair adalah salah satu pihak awal yang melakukan pernyataan diri sebagai khalifah dan menjadi khalifah paralel saat Wangsa Umayyah di Damaskus juga masih menyandang gelar ini. Ayahnya adalah Zubair bin Awwam, keponakan Khadijah binti Khuwailid dari jalur ayah dan sepupu Nabi Muhammad dari jalur ibu. Ibunya adalah Asma', putri Khalifah Abu Bakar dan kakak ipar Nabi Muhammad.
'Abdullah bin Zubair pada awalnya menolak kesetiaan kepada khalifah setelah Mu'awiyah bin Abu Sufyan melantik putranya sendiri, Yazid, sebagai putra mahkota. Setelah Yazid mangkat setelah tiga tahun berkuasa dan kekuasaan diwariskan kepada putranya, Mu'awiyah II, 'Abdullah bin Zubair menyatakan dirinya sebagai amirul-mu'minin, salah satu gelar lain untuk khalifah.[36][37] Kedudukannya sebagai khalifah diakui oleh masyarakat Hijaz, Yaman, Mesir, dan Iraq. Kekuasaan 'Abdullah bin Zubair berakhir saat Khalifah 'Abdul Malik bin Marwan mengutus Al-Hajjaj bin Yusuf untuk menundukkannya. Al-Hajjaj mengepung Makkah selama sekitar enam bulan dan banyak dari para pengikut 'Abdullah bin Zubair menyerah pada masa ini. 'Abdullah bin Zubair tetap menolak untuk menyerah dan melanjutkan perlawanan sampai dia terbunuh pada Oktober atau November 692.[36][38]
Wangsa Fatimiyah

Wangsa Fatimiyah adalah dinasti beraliran Syi'ah Ismailiyah yang menyatakan diri sebagai keturunan putri bungsu Nabi Muhammad, Fatimah az-Zahra. Mereka mengklaim gelar khalifah mulai tahun 909 dan menjadi khalifah pesaing dari Wangsa Abbasiyah yang bertakhta di Mesopotamia. Pada masa puncaknya, Fatimiyah menguasai kawasan Afrika Utara, Sisilia, Syam, dan Hijaz. Fatimiyah awalnya berkuasa di kawasan Tunisia dan kemudian memindahkan ibukotanya di Kairo setelah Mesir ditaklukkan pada 969.[39]
Fatimiyah membentuk tentara berlandas etnis yang terbukti membawa keberhasilan di medan perang, tetapi tidak dalam ranah politik dalam negeri. Perselisihan antar kelompok militer menjadikan kekuasaan dinasti ini merosot dengan cepat pada akhir abad kesebelas dan abad kedua belas. Shalahuddin mengakhiri kekuasaan dinasti ini pada 1171, mendirikan dinasti Al-Ayyubi yang menyatakan kesetiaan pada Wangsa Abbasiyah.[40] Terdapat empat belas khalifah dari Wangsa Fatimiyah dan mereka berkuasa dalam rentang waktu lebih dari dua setengah abad.
Khalifah di Kordoba

Semenanjung Iberia, juga dikenal dengan Al-Andalusia, telah menjadi bagian dari kekhalifahan pada masa Umayyah. Setelah kekuasaan Umayyah di Syam runtuh pada 750, 'Abdurrahman ad-Dakhil pergi ke semenanjung Iberia dan menjadi penguasa di sana setelah menggulingkan penguasa sebelumnya, memerintah kawasan Iberia dari kota Kordoba. Meski moyangnya telah menyandang gelar khalifah selama hampir seabad saat berkuasa di Syam, anggota Wangsa Umayyah yang berkuasa di Iberia awalnya hanya menyandang gelar "amir" (setara dengan 'adipati') dan mengakui klaim pihak Abbasiyah sebagai pemimpin seluruh umat Islam,[41] meski perselisihan di antara kedua belah pihak masih berlanjut.
Namun setelah Fatimiyah yang mengklaim gelar khalifah mulai mengancam kekuasaan Umayyah di Al-Andalus, keturunan 'Abdurrahman ad-Dakhil, 'Abdurrahman III, menyatakan dirinya sebagai khalifah pada 16 Januari 929.[42] Hal ini menjadikan terdapat tiga pihak yang mengklaim gelar khalifah: Abbasiyah di Baghdad, Fatimiyah yang berpusat di Mesir, dan penguasa di Kordoba. Tak hanya dalam masalah kekuasaan, Kordoba juga menjadi pesaing Baghdad terkait perannya sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya.[43][44] Pada masa Al-Hakam II, perpustakaan istana memiliki 500.000 volume buku. Sebagai perbandingan, Biara Santo Gallen di Swiss hanya memiliki 100 volume.[45] Universitas di Kordoba juga menjadi yang paling terkenal di dunia kala itu, didatangi murid Muslim ataupun Kristen dari segala penjuru Eropa Barat. Universitas ini melahirkan seratus lima puluh penulis. Universitas dan perpustakaan lain juga tersebar di kawasan Iberia pada masa ini.[46]
Pada keberjalanannya, kekuasaan Wangsa Umayyah di Andalusia semakin melemah, menjadikan Wangsa Hammud, sebuah dinasti Muslim Arab-Berber, mampu merebut tampuk kekhalifahan selama beberapa waktu.[45] Umayyah dapat mengambil kembali status khalifah, tetapi negara tersebut sudah sangat melemah dengan beberapa wilayah telah lepas dari kendali khalifah. Penggulingan Hisyam III pada 1031 menjadi akhir dari riwayat khalifah di Kordoba. Setelahnya, wilayah yang dulu dikuasai khalifah terpecah menjadi negara-negara kecil yang disebut taifa.[47] Meski khalifah di Kordoba hanya bertahan selama sekitar satu abad, kekuasaan umat Muslim di Andalusia masih berlanjut sampai Wangsa Nasrid penguasa Granada dikalahkan pihak Katolik Spanyol pada 1492.
Keruntuhan kekhalifahan
Setelah Sultan Abdül Hamid II digulingkan pada 1909, dua sultan penerusnya hampir kehilangan kekuatan politik sepenuhnya dan hanya berperan sebagai lambang kepala negara semata tanpa kekuasaan yang nyata. Kesultanan Utsmani kehilangan sebagian besar wilayahnya setelah kalah dalam Perang Dunia I, menjadikan hanya menguasai kawasan Anatolia dan ujung tenggara Balkan. Istambul (Konstantinopel) dikuasai Britania Raya setelahnya, menciptakan sebuah kevakuman politik dengan menawan banyak pejabat negara dan menutup kantor-kantor pemerintahan dengan paksa.
Kekalahan Utsmani menimbulkan reaksi yang disebut Gerakan Khilafat sebagai bentuk kekhawatiran akan kesatuan umat Islam. Meski gerakan ini didengungkan di berbagai belahan dunia Islam, kegiatannya paling banyak dilangsungkan di India sehingga juga disebut Gerakan Muslim India. Sebagai pemenang perang, pihak Eropa menjanjikan untuk melindungi status penguasa Utsmani sebagai khalifah, tetapi Perjanjian Sèvres yang ditandatangani pada 1920 menjadikan kawasan Iraq, Syam, dan Mesir diserahkan pada negara-negara Eropa.
Pada 1 November 1922, Majelis Agung Nasional Turki secara resmi membubarkan Kesultanan Utsmani. Sultan terakhirnya, Mehmed VI, diasingkan ke Malta. Setelah pembubaran Utsmani, Republik Turki yang berasaskan sekuler didirikan dengan Mustafa Kemal sebagai presiden pertamanya.
Meski demikian, Mustafa Kemal tidak berani membubarkan kekhalifahan demi menjaga dukungan rakyat. Meski sudah kehilangan peran politiknya sejak lama, khalifah tetap dipandang sebagai lambang pemersatu umat Islam Sunni seluruh dunia. Pembubaran kesultanan juga lebih mudah lantaran keberlangsungan kekhalifahan saat itu menyenangkan para pendukung kesultanan. Pada 17 November 1922, Majelis Agung Nasional Turki mengangkat sepupu Mehmed VI sebagai Khalifah Abdül Mejid II. Hal ini menjadikan Abdül Mejid II sebagai satu-satunya khalifah dari Wangsa Utsmani yang tidak merangkap sebagai sultan.
Keadaan ini menjadikan keadaan di Turki terbelah dengan pemerintahan republik yang baru di satu sisi dan pemerintahan Islam yang dikepalai khalifah di sisi lain. Khalifah memiliki perbendaharaan pribadi dan pelayanan pribadi, termasuk personel militer. Abdül Mejid II juga menerima duta asing, juga turut serta dalam upacara dan perayaan resmi. Mustafa Kemal mengkhawatirkan bahwa Abdül Mejid II nantinya akan memegang kendali urusan negara selayaknya seorang sultan.
Dalam keadaan seperti ini, Maulana Mohammad Ali dan Maulana Shaukat Ali yang merupakan pemimpin Gerakan Khilafat menyebarkan pamflet yang menyerukan rakyat Turki untuk mendukung kekhalifahan demi kepentingan Islam. Oleh pihak republik, hal ini dipandang sebagai campur tangan pihak asing yang dapat membahayakan keamanan negara. Hal ini menjadi pembenaran Mustafa Kemal untuk mengakhiri kekhalifahan. Pada 3 Maret 1924, Majelis Agung Nasional Turki membubarkan kekhalifahan dan mengasingkan Abdül Mejid II beserta para pangeran dan putri Wangsa Utsmaniyah dari Republik Turki.
Pasca pembubaran kekhalifahan
Banyak pihak mempertanyakan keabsahan pembubaran kekhalifahan oleh pihak Turki secara sepihak. Syarif Makkah, Husain bin Ali, mengklaim gelar khalifah untuk dirinya sendiri. Namun pengakuannya tidak diterima oleh semua umat Muslim. Setelah Husain turun takhta, putranya tidak melanjutkan klaim ayahnya sebagai khalifah.
Pada 1926, diselenggarakan pertemuan di Kairo terkait upaya untuk kembali menegakkan kekhalifahan, tetapi banyak negara Muslim yang tidak hadir dan tidak ada tindakan nyata setelah pertemuan tersebut.
Pada perkembangan selanjutnya, gelar Amir al-Mukmin disandang oleh Raja Maroko dan Mullah Mohammed Omar, pemimpin rezim Taliban di Afganistan, tetapi kebanyakan Muslim di luar daerah kekuasaan mereka menolak untuk mengakuinya. Saat ini banyak pecahan negara-negara muslim yang membentuk Organisasi Konferensi Islam atau OKI, sebuah organisasi internasional dengan pengaruh yang terbatas yang didirikan pada tahun 1969 beranggotakan negara-negara mayoritas Muslim.
Landasan agama
Dalil al-Qur'an
Di dalam al-Quran memang tidak terdapat istilah Daulah yang berarti negara. Tetapi dial-Quran terdapat ayat yang menunjukkan wajibnya umat memiliki pemerintahan/negara (ulil amri). Allah berfirman:
- Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).
Ayat di atas telah memerintahkan kita untuk menaati Ulil amri. Yang dalam hal ini dimaksudkan adalah pemerintahan yang sah.
Maka menjadi jelas bahwa mentaati ulil amri adalah suatu perkara yang wajib.
Dalil as-Sunnah tentang Khalifah
- Abdullah bin Umar meriwayatkan, "Aku mendengar Rasulullah mengatakan, ‘Barangsiapa melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya dia akan menemui Allah pada Hari Kiamat dengan tanpa alasan. Dan barangsiapa mati sedangkan di lehernya tak ada bai’at (kepada Khalifah) maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah." [HR. Muslim].
- Muhammad mewajibkan adanya bai’at pada leher setiap muslim dan menyifati orang yang mati dalam keadaan tidak berbai’at seperti matinya orang-orang jahiliyyah. Padahal bai’at hanya dapat diberikan kepada Khalifah, bukan kepada yang lain. Jadi hadis ini menunjukkan kewajiban mengangkat seorang Khalifah, yang dengannya dapat terwujud bai’at di leher setiap muslim. Sebab bai’at baru ada di leher kaum muslimin kalau ada Khalifah/Imam yang memimpin Khilafah.
- Muhammad bersabda: "Bahwasanya Imam itu bagaikan perisai, dari belakangnya umat berperang dan dengannya umat berlindung." [HR. Muslim]
- Muhammad bersabda: "Dahulu para nabi yang mengurus Bani Israil. Bila wafat seorang nabi diutuslah nabi berikutnya, tetapi tidak ada lagi nabi setelahku. Akan ada para Khalifah dan jumlahnya akan banyak. Para Sahabat bertanya,’Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi menjawab,’Penuhilah bai’at yang pertama dan yang pertama itu saja. Penuhilah hak-hak mereka. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka." [HR. Muslim].
- Muhammad bersabda: "Bila seseorang melihat sesuatu yang tidak disukai dari amirnya (pemimpinnya), maka bersabarlah. Sebab barangsiapa memisahkan diri dari penguasa (pemerintahan Islam) walau sejengkal saja lalu ia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah." [HR. Muslim].
Hadis pertama dan kedua merupakan pemberitahuan (ikhbar) dari Muhammad bahawa seorang Khalifah adalah laksana perisai, dan bahawa akan ada penguasa-penguasa yang memerintah kaum muslimin. Pernyataan Muhammad bahawa seorang Imam itu laksana perisai menunjukkan pemberitahuan tentang adanya faedah-faedah keberadaan seorang Imam, dan ini merupakan suatu tuntutan (thalab). Sebab, setiap pemberitahuan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, apabila mengandung celaan (adz dzamm) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk meninggalkan (thalab at tarki), atau merupakan larangan (an nahy); dan apabila mengandung pujian (al mad-hu) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan (thalab al fi’li). Dan kalau pelaksanaan perbuatan yang dituntut itu menyebabkan tegaknya hukum syara’ atau jika ditinggalkan mengakibatkan terabaikannya hukum syara’, maka tuntutan untuk melaksanakan perbuatan itu bererti bersifat pasti (fardlu). Jadi hadis pertama dan kedua ini menunjukkan wajibnya Khilafah, sebab tanpa Khilafah banyak hukum syara’ akan terabaikan.
Hadis ketiga menjelaskan keharaman kaum muslimin keluar (memberontak, membangkang) dari penguasa (as sulthan). Berarti keberadaan Khilafah adalah wajib, sebab kalau tidak wajib tidak mungkin Muhammad sampai begitu tegas menyatakan bahwa orang yang memisahkan diri dari Khilafah akan mati jahiliyah. Jelas ini menegaskan bahawa mendirikan pemerintahan bagi kaum muslimin statusnya adalah wajib.
Muhammad bersabda pula : "Barangsiapa membai’at seorang Imam (Khalifah), lalu memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah hatinya, hendaklah ia mentaatinya semaksimal mungkin. Dan jika datang orang lain hendak mencabut kekuasaannya, penggallah leher orang itu." [HR. Muslim].
Dalam hadis ini Muhammad telah memerintahkan kaum muslimin untuk menaati para Khalifah dan memerangi orang-orang yang merebut kekuasaan mereka. Perintah Rasulullah ini berarti perintah untuk mengangkat seorang Khalifah dan memelihara kekhilafahannya dengan cara memerangi orang-orang yang merebut kekuasaannya. Semua ini merupakan penjelasan tentang wajibnya keberadaan penguasa kaum muslimin, iaitu Imam atau Khalifah. Sebab kalau tidak wajib, nescaya tidak mungkin Muhammad memberikan perintah yang begitu tegas untuk memelihara eksistensinya, iaitu perintah untuk memerangi orang yang akan merebut kekuasaan Khalifah.
Dengan demikian jelaslah, dalil-dalil As Sunnah ini telah menunjukkan wajibnya Khalifah bagi kaum muslimin.
Dalil Ijma’ Sahabat
Sebagai sumber hukum Islam ketiga, Ijma’ Sahabat menunjukkan bahwa mengangkat seorang Khalifah sebagai pemimpin pengganti Muhammad hukumnya wajib. Mereka telah sepakat mengangkat Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khathtab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
Ijma’ Sahabat yang menekankan pentingnya pengangkatan Khalifah, tampak jelas dalam kejadian bahawa mereka menunda kewajiban menguburkan jenazah Muhammad dan mendahulukan pengangkatan seorang Khalifah pengganti dia. Padahal menguburkan mayat secepatnya adalah suatu kewajiban dan diharamkan atas orang-orang yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah untuk melakukan kesibukan lain sebelum jenazah dikebumikan. Namun, para Sahabat yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah Muhammad ternyata sebagian di antaranya justru lebih mendahulukan usaha-usaha untuk mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah Rasulullah. Sedangkan sebagian Sahabat lain mendiamkan kesibukan mengangkat Khalifah tersebut, dan ikut pula bersama-sama menunda kewajiban menguburkan jenazah Muhammad sampai dua malam, padahal mereka mampu mengingkari hal ini dan mampu mengebumikan jenazah Nabi secepatnya. Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan (ijma’) mereka untuk segera melaksanakan kewajiban mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah. Hal itu tak mungkin terjadi kecuali jika status hukum mengangkat seorang Khalifah adalah lebih wajib daripada menguburkan jenazah.
Demikian pula bahawa seluruh Sahabat selama hidup mereka telah bersepakat mengenai kewajiban mengangkat Khalifah. Walaupun sering muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang tepat untuk dipilih dan diangkat menjadi Khalifah, namun mereka tidak pernah berselisih pendapat sedikit pun mengenai wajibnya mengangkat seorang Khalifah, baik ketika wafatnya Muhammad maupun ketika pergantian masing-masing Khalifah yang empat. Oleh karena itu Ijma’ Sahabat merupakan dalil yang jelas dan kuat mengenai kewajiban mengangkat Khalifah.
Dalil Dari Kaidah Syar’iyah
Ditilik dari analisis usul fiqh, mengangkat Khalifah juga wajib. Dalam usul fikih dikenal kaidah syar’iyah yang disepakati para ulama:
"Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula keberadaannya."[butuh rujukan] Menerapkan hukum-hukum yang berasal dari Allah dalam segala aspeknya adalah wajib. Sementara hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Maka dari itu, berdasarkan kaidah syar’iyah tadi, eksistensi Khilafah hukumnya menjadi wajib.
Jelaslah, berbagai sumber hukum Islam tadi menunjukkan bahwa menegakkan Daulah Khilafah merupakan kewajipan dari Allah atas seluruh kaum muslimin.
Pendapat Para Ulama
Seluruh imam mazhab dan para mujtahid besar tanpa kecuali telah bersepakat bulat akan wajibnya Khilafah (atau Imamah) ini. Syaikh Abdurrahman Al Jaziri menegaskan hal ini dalam kitabnya Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, jilid V, hal. 416:
- "Para imam mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad) --rahimahumullah-- telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) itu wajib adanya, dan bahawa ummat Islam wajib mempunyai seorang imam (khalifah,) yang akan meninggikan syiar-syiar agama serta menolong orang-orang yang tertindas dari yang menindasnya..."
Tidak hanya kalangan Ahlus Sunnah saja yang mewajibkan Khilafah, bahkan seluruh kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah (termasuk Khawarij dan Mu’tazilah) tanpa kecuali bersepakat tentang wajibnya mengangkat seorang Khalifah. Kalau pun ada segelintir orang yang tidak mewajibkan Khilafah, maka pendapatnya itu tidak perlu dianggap, karena bertentangan dengan nas-nas syara’ yang telah jelas.
Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Authar jilid 8 hal. 265 menyatakan: "Menurut golongan Syiah, minoritas Mu’tazilah, dan Asy A’riyah, (Khilafah) adalah wajib menurut syara’." Ibnu Hazm dalam Al Fashl fil Milal Wal Ahwa’ Wan Nihal juz 4 hal. 87 mengatakan: "Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah, seluruh Murji`ah, seluruh Syi’ah, dan seluruh Khawarij, mengenai wajibnya Imamah (Khilafah)."
Bahwa Khilafah adalah sebuah ketentuan hukum Islam yang wajib (bukan haram apalagi bid’ah) dapat kitab temukan dalam khazanah Tsaqafah Islamiyah yang sangat kaya. Berikut ini sekelumit saja referensi yang menunjukkan kewajiban Khilafah: Imam Al Mawardi, Al Ahkamush Shulthaniyah, hal. 5, Abu Ya’la Al Farraa’, Al Ahkamush Shulthaniyah, hal.19, Ibnu Taimiyah, As Siyasah Asy Syar’iyah, hal.161, Ibnu Taimiyah, Majmu’ul Fatawa, jilid 28 hal. 62, Imam Al Ghazali, Al Iqtishaad fil I’tiqad,hal. 97, Ibnu Khaldun, Al Muqaddimah, hal.167, Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, juz 1 hal.264, Ibnu Hajar Al Haitsami, Ash Shawa’iqul Muhriqah, hal.17, Ibnu Hajar A1 Asqallany, Fathul Bari, juz 13 hal. 176, Imam An Nawawi, Syarah Muslim, juz 12 hal. 205, Dr. Dhiya’uddin Ar Rais, Al Islam Wal Khilafah, hal.99, Abdurrahman Abdul Khaliq, Asy Syura, hal.26, Abdul Qadir Audah, Al Islam Wa Audla’una As Siyasiyah, hal. 124, Dr. Mahmud Al Khalidi, Qawaid Nizham Al Hukum fil Islam, hal. 248, Sulaiman Ad Diji, Al Imamah Al ‘Uzhma, hal.75, Muhammad Abduh, Al Islam Wan Nashraniyah, hal. 61, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Namun ada pula buku yang menyatakan bahwa kekhalifahan tidak wajib hukumnya, seperti Al Islam Wa Usululul Hukm oleh Ali Abdur Raziq, Mabadi` Nizham Al Hukmi fil Islam oleh Abdul Hamid Mutawalli, Tidak Ada Negara Islam oleh Nurcholish Madjid.
Daftar Khalifah
Lihat pula
Rujukan
- ^ Omar Hossino. Classical Islamic Views on Human Nature, Political Authority, and International Relations, 2006.
- ^ Omar Hossino (2006). "Classical Islamic Views on Human Nature, Political Authority, and International Relations". Unpublished.
- ^ Gianluca Paolo Parolin, Citizenship in the Arab World: Kin, Religion and Nation-state (Amsterdam University Press, 2009), 52.
- ^ Hourani, p. 23.
- ^ Ahmed, Nazeer, Islam in Global History: From the Death of Prophet Muhammad to the First World War, American Institute of Islamic History and Cul, 2001, p. 34. ISBN 0-7388-5963-X.
- ^ Ochsenweld, William; Fisher, Sydney Nettleton (2004). The Middle East: A History (edisi ke-6th). New York: McGraw Hill. ISBN 978-0-07-244233-5.
- ^ The Cambridge History of Islam, ed. P.M. Holt, Ann K.S. Lambton, and Bernard Lewis, Cambridge, 1970
- ^ Lapidus 2002, hlm. 47.
- ^ Holt, Lambton & Lewis 1970, hlm. 70–72.
- ^ Tabatabaei 1979, hlm. 50–75 and 192.
- ^ Donaldson, Dwight M. (1933). The Shi'ite Religion: A History of Islam in Persia and Irak (PDF). Burleigh Press. hlm. 66–78.
- ^ Jafri, Syed Husain Mohammad (2002). The Origins and Early Development of Shi’a Islam; Chapter 6. Oxford University Press. ISBN 978-0195793871.
- ^ Ayati, Dr. Ibrahim. "A Probe into the History of Ashura'". Al-Islam.org. Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project.
- ^ John Esposito (1992)
- ^ Cavendish, Marshall (2010). "6". Islamic Beliefs, Practices, and Cultures. hlm. 129. ISBN 978-0-7614-7926-0.
- ^ Blankinship, Khalid Yahya (1994), The End of the Jihad State, the Reign of Hisham Ibn 'Abd-al Malik and the collapse of the Umayyads, State University of New York Press, hlm. 37, ISBN 0-7914-1827-8
- ^ Previté-Orton (1971), pg 236
- ^ "Umayyad dynasty | Islamic history". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-03-26.
- ^ "What is the difference between Sunni and Shia Muslims?". The Economist. 28 May 2013.
- ^ Previté-Orton (1971), vol. 1, pg. 239
- ^ Canfield, Robert L. (2002). Turko-Persia in Historical Perspective. Cambridge University Press. hlm. 5. ISBN 9780521522915.
- ^ Gregorian 2003
- ^ Huff 2003, hlm. 48
- ^ Grant & Clute 1999, hlm. 51.
- ^ Clinton 2000, hlm. 15–16
- ^ Ahmed 1992, hlm. 112–15.
- ^ Youshaa Patel (2013). "Seclusion". The Oxford Encyclopedia of Islam and Women. Oxford: Oxford University Press. ((Perlu berlangganan (help)).
- ^ a b Eleanor Abdella Doumato (2009). "Seclusion". Dalam John L. Esposito. The Oxford Encyclopedia of the Islamic World. Oxford: Oxford University Press. ((Perlu berlangganan (help)).
- ^ The Cambridge History of Islam I: The Central Islamic Lands (dalam bahasa Turki). Cambridge University Press. 1970.
- ^ M.Sükrü Hanioglu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, 130.
- ^ a b Takkush, Mohammed Suhail, "The Ottoman's History" pp.489,490
- ^ Lewis.B, "The Emergence of Modern Turkey" Oxford, 1962, p.337
- ^ a b Kemal H. Karpat (2001). The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State. Oxford University Press. hlm. 235. ISBN 978-0-19-513618-0.
- ^ Moshe Yegar (1 January 2002). Between Integration and Secession: The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar. Lexington Books. hlm. 397. ISBN 978-0-7391-0356-2.
- ^ Dr. Bayram Kodaman, The Hamidiye Light Cavalry Regiments (Abdullmacid II and Eastern Anatolian Tribes)
- ^ a b Gibb 1960, p. 55.
- ^ Hawting 1986, p. 47.
- ^ Gibb 1960, p. 54.
- ^ Abbasid Belles Lettres. Cambridge University Press; 30 March 1990. ISBN 978-0-521-24016-1. p. 13.
- ^ Baer, Eva (1983). Metalwork in Medieval Islamic Art. SUNY Press. hlm. xxiii. ISBN 9780791495575.
- ^ O'Callaghan, J. F. (1983). A History of Medieval Spain. Ithaca: Cornell University Press. hlm. 119.
- ^ Barton, 38.
- ^ Barton, 40–41.
- ^ Barton, 42.
- ^ a b Catlos, Brain A. (2014). Infidel Kings and Unholy Wars: Faith, Power, and Violence in the Age of Crusades and Jihad. New York: Farrar, Straus, and Giroux. p. 30.
- ^ Francis Preston Venable, A Short History of Chemistry (1894) p. 21.
- ^ Chejne, Anwar G. (1974). Muslim Spain: Its History and Culture. Minneapolis: The University of Minnesota Press. hlm. 43–49. ISBN 0816606889.
Daftar pustaka
- Ahmed, Leila (1992). Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. Yale University Press. ISBN 978-0-300-05583-2.
- Arnold, T. W. (1993). "Khalīfa". Dalam Houtsma, M. Th. E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913–1936. Volume IV. Leiden: BRILL. hlm. 881–885. ISBN 978-90-04-09790-2. Diakses tanggal 2010-07-23.
- Barton, Simon (2004). A History of Spain. New York: Palgrave MacMillan. ISBN 0333632575.
- Clinton, Jerome W. (2000). Talattof, Kamran; Clinton, Jerome W., ed. The Poetry of Nizami Ganjavi: Knowledge, Love, and Rhetoric. Houndmills, UK: Palgrave Macmillan. ISBN 0-3122-2810-4. LCCN 99056710.
- Crone, Patricia, and Martin Hinds. God's Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. ISBN 0-521-32185-9.
- Donner, Fred. The Early Islamic Conquests. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981. ISBN 0-691-05327-8.
- Gibb, H. A. R. (1960). "ʿAbd Allāh ibn al-Zubayr". Dalam Gibb, H. A. R.; Kramers, J. H.; Lévi-Provençal, E.; Schacht, J.; Lewis, B.; Pellat, Ch. Encyclopaedia of Islam. Volume I: A–B (edisi ke-2). Leiden: E. J. Brill. hlm. 54–55. OCLC 495469456.
- Grant, John; Clute, John (1999). "The Encyclopedia of Fantasy". Arabian fantasy. New York, NY: St. Martin's Press. ISBN 0-312-19869-8. LCCN 96037472.
- Gregorian, Vartan (2003). Islam: A Mosaic, Not a Monolith. Washington, DC: Brookings Institution Press. hlm. 26–38. ISBN 0-8157-3282-1. LCCN 2003006189.
- Hawting, G. R. (2000) [1986]. The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750 (edisi ke-2nd). London and New York: Routledge. ISBN 0-415-24073-5.
- Holt, P.M.; Lambton, Ann K.S.; Lewis, Bernard, ed. (1970). Cambridge History of Islam. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-29135-4.
- Hourani, Albert. A History of the Arab Peoples, Faber and Faber, 1991.
- * Huff, Toby E. (2003). The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West (edisi ke-2nd). Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 0-5218-2302-1. LCCN 2002035017.
- Lapidus, Ira (2002). A History of Islamic Societies (edisi ke-2nd). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-77933-3.
- *Previté-Orton, C. W (1971). The Shorter Cambridge Medieval History. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tabatabaei, Sayyid Mohammad Hosayn (1979). Shi'ite Islam. Suny press. ISBN 978-0-87395-272-9.| Translated by Seyyed Hossein Nasr.
